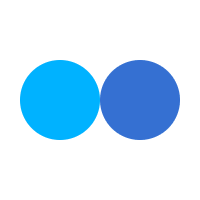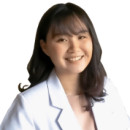1. Fishman JA. Infection in Organ Transplantation. Am J Transplant. 2017 Apr;17(4):856-879. doi: 10.1111/ajt.14208.
2. Fishman JA. Opportunistic infections--coming to the limits of immunosuppression? Cold Spring Harb Perspect Med. 2013 Oct 1;3(10):a015669. doi: 10.1101/cshperspect.a015669.
3. Fishman JA. Infection in solid‐organ transplant recipients. N Engl J Med 2007; 357: 2601–2614.
4. Wilck MB, Zuckerman RA. Herpes simplex virus in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013; 13(Suppl 4): 121–127.
5. Koo S, Gagne LS, Lee P, et al. Incidence and risk factors for herpes zoster following heart transplantation. Transpl Infect Dis 2014; 16: 17–25.
6. Hamaguchi Y, Mori A, Uemura T, et al. Incidence and risk factors for herpes zoster in patients undergoing liver transplantation. Transpl Infect Dis 2015; 17: 671–678.
7. Eid AJ, Razonable RR. New developments in the management of cytomegalovirus infection after solid organ transplantation. Drugs 2010; 70: 965–981.
8. Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. International consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid organ transplantation. Transplantation 2010; 89: 779–795.
9. Dharnidharka VR, Lamb KE, Gregg JA, Meier‐Kriesche HU. Associations between EBV serostatus and organ transplant type in PTLD risk: An analysis of the SRTR National Registry Data in the United States. Am J Transplant 2012; 12: 976–983.
10. Dharnidharka VR. Peripheral blood Epstein‐Barr viral nucleic acid surveillance as a marker for posttransplant cancer risk. Am J Transplant. 2016. doi: 10.1111/ajt.13982.
11. Hirsch HH, Randhawa P. BK polyomavirus in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013; 13(Suppl 4): 179–188.
12. Pappas PG, Alexander BD, Andes DR, et al. Invasive fungal infections among organ transplant recipients: Results of the Transplant‐Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). Clin Infect Dis 2010; 50: 1101–1111.
13. Steinbach WJ, Marr KA, Anaissie EJ, et al. Clinical epidemiology of 960 patients with invasive aspergillosis from the PATH Alliance registry. J Infect 2012; 65: 453–464.
14. Munoz P, Rodriguez C, Bouza E, et al. Risk factors of invasive aspergillosis after heart transplantation: Protective role of oral itraconazole prophylaxis. Am J Transplant 2004; 4: 636–643.
15. Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2016; 63: e1–e60.
16. Martin SI, Fishman JA. Pneumocystis pneumonia in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013; 13(Suppl 4): 272–279.
17. Lu Y, Ling G, Qiang C, et al. PCR diagnosis of Pneumocystis pneumonia: A bivariate meta‐analysis. J Clin Microbiol 2011; 49: 4361–4363.
18. Asberg A, Humar A, Rollag H, et al. Oral valganciclovir is noninferior to intravenous ganciclovir for the treatment of cytomegalovirus disease in solid organ transplant recipients. Am J Transplant 2007; 7: 2106–2113.
19. Allen UD, Preiksaitis JK. Epstein‐Barr virus and posttransplant lymphoproliferative disorder in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013; 13(Suppl 4): 107–120.
20. Savoldo B, Goss J, Liu Z, et al. Generation of autologous Epstein‐Barr virus‐specific cytotoxic T cells for adoptive immunotherapy in solid organ transplant recipients. Transplantation 2001; 72: 1078–1086.
21. Leen AM, Christin A, Myers GD, et al. Cytotoxic T lymphocyte therapy with donor T cells prevents and treats adenovirus and Epstein‐Barr virus infections after haploidentical and matched unrelated stem cell transplantation. Blood 2009; 114: 4283–4292.