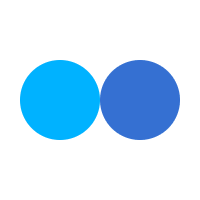Waktu untuk memulai farmakoterapi pada hepatitis B kronik adalah pengetahuan yang penting bagi dokter, karena infeksi virus hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan dunia. Walaupun prevalensi hepatitis B telah menurun dengan adanya vaksinasi, tetapi secara global masih terdapat 350–400 juta orang yang terkena hepatitis B kronik.[1]
Indonesia merupakan negara dengan prevalensi hepatitis B terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Vietnam. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2018, sebanyak 7,1% penduduk Indonesia mengalami hepatitis B kronik. Tingginya morbiditas dan mortalitas yang ditimbulkan hepatitis B menjadi faktor penting untuk memberikan terapi pada saat yang tepat.[2,3]
Terapi Antiviral Menekan Replikasi HBV dan Menurunkan Morbiditas
Tujuan terapi antiviral hepatitis B kronik adalah untuk mencegah perburukan penyakit dan meningkatkan survival. Hepatitis B kronis memiliki perjalanan penyakit dengan episode eksaserbasi periodik, yang terjadi akibat aktivasi sistem imun terhadap hepatosit untuk memberantas virus. Eksaserbasi akut ini dapat menyebabkan terjadinya fibrosis, dan lama-lama berkembang menjadi sirosis hepatis.[4]
Terapi antiviral direkomendasikan pada penderita dewasa hepatitis B kronik fase imun aktif, baik pada HBeAg negatif maupun positif, untuk mengurangi risiko komplikasi terkait hepar. Antiviral yang direkomendasikan adalah interferon (IFN) dan analog nukleotida, seperti entecavir atau tenofovir.[3,5]
Morbiditas dan Mortalitas akibat Hepatitis B Kronik
Sekitar 8–20% pasien hepatitis B kronik diprediksi dapat mengalami sirosis dalam 5 tahun. Kurang lebih 15% akan terkena sirosis kompensata, dan lebih dari 60% pasien dengan sirosis dekompensata akan meninggal dalam 5 tahun.
Selain itu, pasien dengan hepatitis B kronik memiliki risiko terkena karsinoma hepatoselular yang lebih tinggi dibanding populasi umum. Risiko ini semakin tinggi pada pasien dengan viremia tinggi berkepanjangan dan penderita sirosis.[4,6]
Keberhasilan Terapi Antiviral
Secara laboratorium, beberapa parameter digunakan untuk menandakan keberhasilan terapi antiviral hepatitis B kronik. Hal ini dapat dicapai melalui penurunan HBV DNA, serokonversi HBeAg pada pasien dengan HBeAg positif, normalisasi serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT), dan hilangnya HBsAg.
Keberhasilan virologis pada terapi antiviral dengan analog nukleotida didefinisikan sebagai HBV DNA yang tidak dapat dideteksi pada darah, dengan ambang batas bawah deteksi sebesar 10–20 IU/mL. Pada penggunaan interferon, keberhasilan virologis dinyatakan sebagai HBV DNA serum kurang dari 2000 IU/mL, pada penilaian di bulan ke-6 setelah memulai terapi. Keberhasilan terapi antiviral secara biokimia adalah jika nilai SGPT menjadi normal.
Sekitar 0,5% penderita hepatitis B kronik inaktif mengalami klirens HBsAg setiap tahunnya, dan sebagian besar membentuk antibodi HBsAg atau anti-HBs. Klirens HBsAg, dengan ambang batas bawah deteksi sebesar 0,05 IU/mL, dapat mengurangi risiko terjadinya karsinoma hepatoselular. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.[7,8]
Antiviral pada Fase Imun Aktif Mendorong Serokonversi HBeAg
Semua pasien hepatitis B kronik tanpa sirosis dengan HBV DNA >2.000 IU/mL, SGOT di atas nilai normal, yaitu 40 IU/mL, disertai dengan nekroinflamasi sedang hingga berat, dapat dipertimbangkan untuk menerima terapi antiviral. Biopsi hepar merupakan baku emas untuk memperkirakan keparahan penyakit, tetapi jarang dilakukan sebab bersifat invasif.
Pasien dengan nilai HBV DNA >20.000 IU/mL dan SGOT meningkat 2 kali dari nilai normal dapat memulai terapi antiviral tanpa melakukan biopsi hepar. Terapi juga boleh diberikan pada pasien dengan HBV DNA >2.000 IU/mL yang mengalami fibrosis sedang, meskipun nilai SGOT normal.
Dalam beberapa studi observasional ditemukan pemberian interferon dan analog nukleotida memberikan efek jangka panjang mencegah terjadinya sirosis dan karsinoma hepatoselular, tetapi hanya analog nukleotida yang menurunkan laju dekompensasi dan kematian.
Keputusan untuk memulai terapi juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi progresivitas penyakit dan risiko karsinoma hepatoselular. Beberapa faktor tersebut, antara lain usia pasien di atas 40 tahun, riwayat keluarga dengan sirosis atau karsinoma hepatoselular, adanya manifestasi ekstrahepatik, serta kebutuhan terkait okupansi, misalnya tenaga kesehatan yang berisiko menularkan ke pasien.[3,4,7]
Waktu Penghentian Terapi Antiviral
Luaran akhir yang ingin dicapai pada terapi antiviral hepatitis B kronik adalah hilangnya HBsAg, dengan atau tanpa pembentukan anti-HBs. Namun, meskipun telah menjalani pengobatan dengan nucleos(t)ide analogue (NA) selama 10 tahun, luaran klinis ini hanya dapat dicapai pada 1–5% pasien.[9]
Respon virologis yang dipertahankan setelah penghentian terapi (sustained off-therapy virological response), baik menggunakan interferon maupun NA, memiliki definisi nilai HBV DNA di bawah 2.000 IU/mL, setidaknya 12 bulan setelah antiviral dihentikan. Penilaian dengan SGPT sulit untuk dilakukan, sebab terkadang SGPT dapat meningkat secara transien pada sebagian pasien hepatitis kronik dalam 1 tahun pertama setelah penghentian terapi.[10]
Rekomendasi dari European Association for the Study of the Liver (EASL) tahun 2017 adalah terapi antiviral dengan NA dapat dihentikan pada pasien HBeAg negatif, tanpa sirosis yang telah mencapai supresi virologis selama lebih dari 3 tahun sejak terapi. Penghentian hanya boleh dilakukan jika pemantauan klinis secara ketat dapat dilakukan setelah pasien menghentikan terapi.[10]
Meskipun demikian, banyak dokter masih enggan untuk menghentikan NA, sebab ada kemungkinan terjadi viral rebound setelah antiviral dihentikan. Pada 55–70% pasien, serum HBV DNA dapat meningkat kembali lebih dari 2.000 IU/mL. Namun, relaps ini tidak selalu disertai dengan peningkatan enzim SGPT.[9,11]
Mayoritas pasien yang mencapai sustained off-therapy response setelah menerima interferon, akan berada dalam kondisi yang cukup stabil setidaknya untuk 5 tahun. Pada pasien-pasien ini, tidak terjadi perburukan penyakit dan adanya perbaikan sel hepar secara histologis. Namun, karsinoma hepatoselular masih mungkin terjadi, terutama jika pasien memiliki riwayat sirosis.[10]
Antiviral pada Fase Toleransi Imun
Beberapa penelitian menunjukkan kadar serum DNA HBV berkaitan erat dengan perkembangan karsinoma hepar dan sirosis, genotipe HBV, kadar serum ALT, dan status HBeAg. Akibatnya, banyak pertanyaan yang muncul mengenai manfaat antiviral pada pasien di fase toleransi imun.[12]
Studi-studi terdahulu menemukan bahwa pasien di fase toleransi imun tidak mengalami inflamasi pada hepar, dan nilai SGPT serum normal, sehingga tidak dibutuhkan antiviral. Risiko karsinoma hepatoselular juga relatif rendah. Berbagai pedoman internasional sepakat bahwa terapi antiviral tidak direkomendasikan bagi pasien di fase toleransi imun, dengan nilai SGPT yang normal.[13]
EASL tidak merekomendasikan antiviral bagi pasien di bawah 30 tahun, dengan nilai SGPT yang normal persisten, HBV DNA tinggi, biasanya >107 IU/mL, tidak ada fibrosis hepar, serta tanpa riwayat keluarga dengan sirosis atau karsinoma hepatoselular. Namun, perlu dilakukan pemantauan setiap 3–6 bulan.[10]
American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) juga menyatakan hal yang serupa. Pada pasien HBeAg positif, dengan nilai SGPT normal persisten, perlu dilakukan pemantauan setiap 3–6 bulan. Jika SGPT mengalami kenaikkan, maka pemeriksaan SGPT harus dilakukan lebih sering. HBeAg sebaiknya diperiksa setiap 6–12 bulan.[14]
Secara umum, definisi pasien yang berada di fase toleransi imun adalah HBeAg positif, SGPT normal, HBV-DNA >107– 108 IU/mL, usia di bawah 30 tahun, tanpa inflamasi atau fibrosis pada hepar, serta tidak ada manifestasi ekstrahepatik. Pada pasien seperti ini, pemberian antiviral bisa ditunda, sebab risiko perburukan penyakit kecil. Tata laksana utama adalah pemantauan intensif oleh tenaga medis.[13]
Namun, dokter harus dapat memastikan bahwa pasien sungguh berada pada fase toleransi imun. Jika nilai HBV DNA pasien tidak terlalu tinggi, tetapi SGPT serum normal, tetap pertimbangkan pemberian antiviral.[13]
Antiviral pada Sirosis Hepatis
Pasien dengan peningkatan HBV DNA dan sirosis, baik kompensata maupun dekompensata, harus mendapat terapi antiviral, tanpa mempertimbangkan nilai SGPT. Pada pasien dengan sirosis dekompensata, mulai terapi dengan NA dan lakukan pemeriksaan kelayakan transplantasi hepar.[7,10]
Terdapat bukti klinis bahwa antiviral yang segera diberikan dapat memperbaiki fungsi hepar, meningkatkan survival, dan mengurangi kebutuhan transplantasi hepar. Namun, terapi antiviral pada sirosis tidak mengeliminasi risiko karsinoma hepatoselular, dan surveilans terhadap karsinoma hepatoselular sebaiknya dilanjutkan.[7,10]
Rekomendasi World Health Organization (WHO) tahun 2015 menyebutkan bahwa pasien hepatitis B kronis yang tidak menunjukkan tanda klinis sirosis harus tetap diberikan antiviral, jika berusia 30 tahun, dengan kadar SGPT abnormal secara persisten, dan terdapat bukti replikasi HBV DNA yang tinggi, yaitu di atas 20.000 IU/mL. Bila tidak tersedia pemeriksaan HBV DNA, maka terapi dapat diberikan berdasarkan nilai SGPT yang tidak normal, tanpa memandang status HBeAg.[15]
Kesimpulan
Inisiasi pemberian antiviral pada pasien hepatitis B kronik bergantung pada fase penyakit yang ditentukan dari status HBeAg, kadar DNA HBV, kadar SGPT serum, dan gambaran histopatologis hepar. Pada fase toleransi imun, pasien tidak direkomendasikan untuk mendapat terapi antiviral. Namun, perlu dilakukan pemantauan berkala, setiap 3–6 bulan untuk menilai klinis pasien.
Terapi antiviral dapat dimulai saat fase imun aktif, yaitu saat inflamasi atau fibrosis hepar, yang ditandai dengan peningkatan SGPT serum dan penurunan HBV DNA dari fase toleransi imun. Terapi bertujuan menekan replikasi virus, yang ditandai penurunan DNA HBV, mendorong serokonversi HBeAg menjadi anti-HBe, sampai akhirnya HBsAg hilang, serta menurunkan risiko karsinoma hepatoselular. Semakin cepat serokonversi terjadi, prognosis pasien semakin baik.
Jika sirosis sudah terjadi, baik kompensata maupun dekompensata, antiviral dapat segera diberikan untuk memperbaiki fungsi hepar, meningkatkan survival pasien, dan mencegah keperluan transplantasi hepar.
Direvisi oleh: dr. Livia Saputra