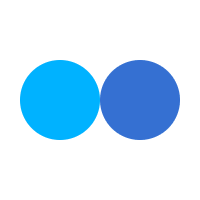Diagnosis Skrofuloderma
Diagnosis skrofuloderma atau scrofuloderma, setelah anamnesis dan pemeriksaan lesi, membutuhkan pemeriksaan penunjang, seperti histopatologi, tes tuberkulin, dan respon positif terhadap pengobatan tuberkulosis. Diagnosis pasti berdasarkan penemuan bakteri Mycobacterium tuberculosis (Mtb) pada kultur jaringan, atau hasil positif pada pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR).[4]
Anamnesis
Pada anamnesis, perlu ditanyakan keluhan klinis yang dialami pasien, riwayat penyakit dahulu atau komorbiditas, dan faktor risiko skrofuloderma. Secara umum, pasien skrofuloderma akan datang dengan keluhan munculnya sebuah benjolan pada kulit, sering kali di area leher, aksila, supraklavikula, atau inguinal.
Referensi
(Konten ini khusus untuk dokter. Registrasi untuk baca selengkapnya)